
Kereta Tiba Pukul Berapa…?
Selasa pagi, 31 Juli 2007, saya dan lima orang teman berangkat menuju Blitar untuk bertakziah kepada salah seorang teman kuliah yang ayahandanya berpulang ke hadirat ilahi. Kami berenam berangkat dari Jember menggunakan kereta api jurusan Malang, karena tidak ada kereta api yang langsung menuju Blitar. Kereta yang menurut jadwal resmi pihak PT. KAI berangkat dari stasiun Jember pada pukul 07.45 WIB, ternyata baru tiba di stasiun setempat pada pukul 08.15 WIB. Merasakan kejenuhan karena menunggu selama setengah jam, saya jadi teringat salah satu bait lagu Iwan Fals yang bunyinya, “…kereta tiba pukul berapa..?” Keresahan hati saya pada saat itu barangkali ada kesamaannya dengan kegelisahan Bang Iwan. Hanya bedanya, Bang Iwan bisa menumpahkan kegelisahannya tersebut dalam bait-bait lagu yang indah, sedangkan saya hanya dapat menggerutu via tulisan ini. Kalau Bang Iwan bisa menjadi tenar dan banyak penggemar, apalah diri saya ini; saya bukan apa-apa dan juga bukan siapa-siapa di mata orang lain (atau setidaknya belum, karena sebenarnya saya juga punya angan untuk menjadi tenar seperti Bang Iwan dengan menyuarakan gelisah dan kegundahannya terhadap realitas sosial masyarakatnya. Meski mungkin saya melalui media dan jalan yang berbeda. Mudah-mudahan…)
Mungkin bagi orang lain yang sudah biasa bepergian dengan menggunakan jasa angkutan kereta api, hal tersebut tak akan menimbulkan kegundahan sama sekali. Tapi tidak bagi orang yang baru pertama kali menggunakan jasa kereta api seperti saya ini. Pada waktu itu saya betul-betul merasa sedikit shock. Mungkin bisa dimaklumi, mengingat pengalaman pertama biasanya membawa konsekuensi tersendiri bagi subjek yang mengalaminya. Mungkin mirip dengan pengalaman malam pertama pengantin baru (menurut kesaksian orang lain yang sudah mengalaminya lho ya, bukan berdasar pengalaman saya. Karena sampai detik saat saya merampungkan tulisan ini, saya masih lajang dan belum punya pengalaman kayak begituan, he he he…). Sayapun akhirnya berpikir, mungkin ini juga merupakan salah satu faktor signifikan penyebab kecelakaan kereta api di Negara tercinta ini, yang telah merenggut korban jiwa tak sedikit. Ketidakdisiplinan waktu seringkali memang harus dibayar amat mahal. Dan bicara soal ketidakdisiplinan, bangsa kita ini adalah jagonya. Lihatlah di lingkungan--dan kehidupan--kampus yang menjadi habitat kita sehari-hari. Dosen yang kerapkali datang terlambat untuk memberikan kuliah, dan juga sebaliknya, tidak sedikit mahasiswa yang baru memasuki ruang kelas di saat perkuliahan sudah dimulai. Seperti kata pepatah lama, “guru kencing berdiri, murid kencing berlari”, dosen telat 15 menit, mahasiswanya telat 30 menit, dst. Padahal ini di kampus, suatu komunitas kehidupan yang--konon katanya--tempatnya orang-orang terdidik dan intelek. Lalu bagaimana dengan kehidupan di tengah-tengah masyarakat yang notabene mereka tak pernah mengenyam pendidikan tinggi dan menjadikan mereka sebagai orang yang awam dalam segala hal? Dan mereka juga tak pernah mengenal tentang pelajaran kedisiplinan waktu sebagaimana yang kita dapatkan sejak dari bangku Sekolah Dasar hingga jenjang Perguruan Tinggi. Saya yakin Anda sudah tahu sendiri jawabannya. Hanya mungkin bedanya, kalau orang-orang “pintar” seperti kita ini mampu menyembunyikan kebiasaan terlambat kita dengan meyebutnya sebagai “kekhilafan” (sekalipun kekhilafan yang diulang-ulang), orang awam akan blak-blakan berkata, ”itu sudah biasa, kenapa takut dengan waktu? Hidup kok dikejar-kejar waktu, santai sajalah…”.
Kehidupan di Atas Kereta
Sepanjang perjalanan di atas kereta menuju kota apel, Malang, saya lebih banyak menyaksikan dan menikmati kehidupan yang saya temui di atas kereta maupun di sekitar sepanjang lintasan kereta, semampu dan sejauh jangkauan mata memandang.
Hiruk pikuk pedagang asongan, para peminta-minta, dan juga pengamen di antara para penumpang di atas kereta membuat saya jadi berpikir tentang banyak hal. Kenapa banyak orang menggantungkan hidupnya dari aktivitas meminta-minta? Tak sedikit di antara mereka adalah orang-orang setengah baya, baik pria maupun wanita. Orang-orang yang sesungguhnya masih kuat untuk bekerja keras memeras keringat membanting tulang, justeru memilih jalan penghidupan yang nista. Saya jadi sedih melihat pemandangan tersebut, lebih miris lagi hati saya ketika meyaksikan di antara para peminta-minta tersebut ternyata beberapa diantaranya adalah anak-anak kecil berusia antara lima sampai sepuluhan tahun. Oh Tuhan, kehidupan macam apa yang sedang saya lihat dan saksikan ini? Anak-anak bangsa yang konon katanya dikaruniai negeri dengan kekayaan alam berlimpah ruah dan tanah yang subur, harus menjadi pengemis untuk menyambung hidupnya. Salah siapa ini? Yang jelas kesalahan tak bisa ditimpakan semata-mata hanya kepada mereka saja. Kita hidup bukan seperti sebuah atom yang bebas tanpa ikatan dengan yang lainnya. Hidup kita laiknya unsur yang terdiri dari atom-atom yang berikatan satu sama lain. Juga seperti halnya senyawa yang tersusun dari ikatan antara berbagai macam unsur. Manusia bukan makhluk individual semata. Ia adalah juga makhluk sosial. Manusia saling berinteraksi dengan manusia lain, dan di dalamnya terjadi interdependensi/kesalingterkaitan antara satu dengan yang lain. Dalam soal pengemis tadi, jelas kesalahan juga ada pada masyarakat, dan lebih-lebih juga adalah kesalahan negara.
Di dalam masyarakat yang sangat materialistis sekarang ini, solidaritas sosial bisa jadi sudah luntur dan sirna. Ego individual semakin menonjol mengalahkan tanggung jawab sosial. Orang hanya sibuk mengejar kepentingannya sendiri, dan sudah tak ambil peduli dengan kehidupan orang-orang di sekitarnya. Dengan nyaman dan bangganya mereka mengenakan pakaian dan perhiasan berharga jutaan, padahal di sekitarnya masih banyak orang yang hanya memiliki pakaian kumal. Juga mereka membangun rumah megah dan mengoleksi mobil mewah, padahal masyarakat di sekitarnya masih tinggal di rumah reyot, dan seringkali harus menahan lapar akibat tak mencukupinya uang untuk membeli cukup beras agar bisa makan tiga kali sehari. Dan yang tak kalah menyedihkan lagi, tak sedikit golongan kaya yang dengan semangatnya berangkat ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji sampai berkali-kali. Padahal jutaan rupiah yang dihambur-hamburkan oleh mereka yang gila berhaji itu tentunya akan lebih bermanfaat bila digunakan untuk menyantuni orang miskin dan anak terlantar. Bukankah ibadah haji hanya diwajibkan satu kali saja seumur hidup? Dan selebihnya adalah sunnah, yang juga harus disesuaikan dengan kondisi individu yang bersangkutan dan masyarakatnya. Apakah orang akan menjadi Haji mabrur seandainya ketika ia berangkat menunaikannya, ada tetangganya yang mengalami kelaparan? Memang, manusia hanya sibuk dengan ritual dan seremonial belaka, dan teramat sedikit yang bisa menarik benang merahnya ke dalam ranah kehidupan sosial. Sungguh ironis dan tragis.
Lantas apa kesalahan negara sehingga banyak warganya harus ‘berprofesi’ sebagai pengemis? Yang jelas ini adalah salah satu potret kegagalan sebuah Negara. Negara yang dibentuk dan didirikan dengan tujuan untuk menjamin hak hidup layak segenap warga negaranya, telah gagal memainkan fungsi tersebut. Negara sudah menjadi semacam preman yang hanya mengamankan kepentingan kaum pemilik modal sebagai majikannya. Rakyat jelata adalah kasta terendah dalam sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. Di atasnya ada para tokoh masyarakat dan tokoh agama. Disusul kemudian kaum pengusaha/konglomerat. Sedang di posisi paling tinggi adalah kaum bangsawan: elit politik dan para birokrat.
Sebagai kaum yang berada pada posisi terendah, sangat wajar bila rakyat hanya dijadikan sebagai ‘tumbal’ bagi roda pembangunan yang hanya akan dinikmati oleh strata sosial atas. Pemukiman digusur untuk dibangun mall, pabrik, dan gedung perkantoran serta apartemen mewah. Pedagang kaki lima di usir atas nama keindahan kota, dst… Lalu muncullah pengangguran baru; sebagian akan menjadi pengemis, pengamen, bahkan pencopet dan penjahat. Lebih ironis dan tragis.
Dalam kasus para pengamen, saya rasa akar persoalannya juga sama dengan para peminta-minta. Disamping kesalahan diri mereka sendiri yang lebih suka ‘bermalas-malasan’, masyarakat dan Negara pun patut untuk dipersalahkan. Namun saya mencoba untuk lebih melihat sisi positif ke dalam diri para pengamen tersebut. Dalam pandangan saya mereka adalah orang-orang yang kreatif dan ulet (sebatas kemampuan mereka) dan lebih memilih ‘menjual’ kebolehannya bermain musik kepada orang lain, dibanding harus menjadi peminta-minta, ataupun preman yang hanya memalak uang dari orang lain. Setidaknya mereka masih mau berpeluh untuk mendapatkan uang.
Ketika mengamati hiruk pikuk para pedagang asongan yang menawarkan dagangannya, saya hanya berpikir betapa tangguh dan uletnya mereka. Tak sedikit di antara mereka adalah para orang lanjut usia dan juga anak-anak kecil. Seharian penuh, bahkan tak jarang sampai larut malam, mereka naik turun dari satu kereta ke kereta lainnya, menyusuri lorong-lorong gerbong diantara deretan kursi-kursi yang dipenuhi penumpang, demi lembaran rupiah untuk nafkah. Mereka adalah sisi lain yang kontras dari manusia Indonesia yang dikenal suka bemalas-malasan dan alon-alon pokok kelakon (biar lambat asal terlaksana, bhs. jawa). Mereka adalah pilar-pilar ekonomi bangsa yang tangguh meski hanya seperti liliput. Buktinya, saat badai krisis ekonomi memporak-porandakan perekonomian Indonesia pada medio 1997, dan membuat usaha-usaha besar kolaps dan gulung tikar, usaha kecil-lah yang mampu bertahan dan sekaligus menjadi penyelamat perekonomian nasional dari jurang kehancuran yang lebih dalam. Namun sayang, mereka tetap saja dipandang sebelah mata. Mereka adalah pahlawan yang tak pernah dihargai oleh negara, dan dalam kebanyakan kasus malah dianak tirikan oleh para pengambil kebijakan.
Pemandangan di Sepanjang Lintasan Kereta
Kegundahan hati melihat kehidupan di atas kereta sedikit terobati dengan memalingkan pandangan menuju jendela kereta. Di sepanjang perjalanan saya meyaksikan melalui jendela betapa indahnya penorama alam yang terlihat laiknya parade gambar (slide show). Sawah yang menghampar luas dan hijau, dan juga para petaninya yang bekerja keras mengolah sawah dan merawat tanamanya. Juga ketika kereta melewati lintasan di atas sungai besar, terlihat betapa indah (dan sekaligus juga menakutkan) aliran air yang menderu-deru terantuk bebatuan.
Namun di samping keindahan panorama alam, hati saya kembali terusik oleh pemandangan berjejalnya pemukiman padat dan kumuh di sepanjang jalan saat kereta melintasi kota. Mereka adalah orang-orang yang tersingkir dari tepian jalan raya kota, akibat pembangunan infrastruktur kota (yang konon katanya demi meningkatkan kesejahteraan hidup seluruh warganya) dan membuat mereka merengsek ke daerah-daerah pinggiran kota; menjadi komunitas tersingkir, menjadi ‘martir’ untuk apa yang kita sebut sebagai “pembangunan”.
Juga para petani penggarap sawah itu, tak banyak mereka yang bisa menggantungkan kemakmuran hidup dari aktivitas bertaninya. Belum ada dalam cerita, petani Indonesia bisa kaya raya, atau minimal hidup makmur. Kecuali petani yang memiliki berhektar-hektar sawah, yang biasanya mereka hanya berperan sebagai majikan tuan tanah; mendapatkan uang berlimpah dari menyewakan tanahnya yang berpuluh, bahkan beratus-ratus hektar tersebut. Sedangkan kebanyakan petani yang hanya memiliki sepetak sawah, dan juga para buruh tani yang tak memiliki tanah pertanian, hidup mereka masih serba kekurangan. Lagi-lagi di sini peran pemerintah patut dipertanyakan. Bagaimana mungkin negeri seluas ini, dengan tanah pertanian yang subur, para petaninya hidup serba kekurangan? Dan Indonesia masih harus mengimpor jutaan ton beras, gula dan komoditas pertanian lainnya dari Negara-negara seperti Vietnam, Thailand, dan India. Kebijakan pemerintah untuk menggenjot angka pertumbuhan ekonomi telah mengorbankan sektor pertanian, dan hanya memihak—secara berlebihan—kepada sektor bisnis besar. Sungguh ini tak kalah ironis, dan juga tragis.
Akhirnya, dalam hati saya merasa beruntung dan sekaligus juga 'menyesal' telah berkesempatan naik kereta api kelas ekonomi bersama kelima teman tersebut. Andaikan saja saya naik kereta api kelas eksekutif, mungkin saya tak akan menjumpai realitas seperti di atas. Saya akan lebih banyak tertidur karena kenyamanan fasilitas yang ada di dalam gerbong kereta eksekutif. [* ]
Wahyu Puspito S, 02 Agustus 2007
Dedicated to everyone, The Big Family of

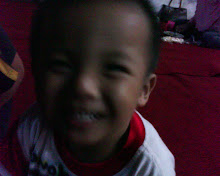
Tidak ada komentar:
Posting Komentar