
Pernahkah kita menemukan gambaran utuh mengenai siapa diri kita di antara banyak manusia di sekitar kita? Apakah deskripsi mengenai diri kita adalah seperti yang tertera—sebatas—di dalam kartu identitas semata? Dan apakah itu sudah cukup membedakan diri kita dari orang lain?
Seperti diungkap Amin Maalouf, intelektual Perancis kelahiran Lebanon dan berdarah Arab, dalam bukunya In the Name of Identity, identitas adalah sesuatu yang membingungkan, dan seringkali juga mengandung dilema. Ia tak pernah tuntas untuk diungkapkan. Sepanjang hidup manusia, identitas terus menerus dirajut dan dari hari ke hari menjadi kian rumit dan tak terpermanai. Tak seorangpun memiliki identitas yang tunggal dan—otomatis juga—final. Anda yang seorang Jawa, Madura ataupun Sunda, misalnya, apakah akan merasa sama dan identik dengan orang lain yang juga sama-sama Jawa, Madura ataupun Sunda? Ada banyak hal yang melekat dalam diri setiap orang, yang membuatnya unik dan khas, yang membedakannya dengan orang lain dan membuatnya tak pernah bisa tergantikan dalam rentang waktu kapanpun. Tak pernah ada dua individu yang sama di dunia ini, dulu, sekarang ataupun nanti.
Kalau Anda berada di negara asing, yang pertama-tama Anda kemukakan kepada orang-orang di sana adalah bahwa Anda seorang Indonesia, bukan orang Aceh, Sulawesi atau Papua. Kalau Anda bertemu sesama orang Indonesia di sana, baru Anda akan menyebut identitas anda yang lain: Anda orang Batak, Anda tinggal di Surabaya, Anda bekerja di perusahaan A, Anda anggota perkumpulan X, dan seterusnya.
Kalau Anda seorang Muslim, Katolik, atau Budha, misalnya, berada di tengah-tengah orang-orang seiman, Anda akan terpicu untuk memunculkan diri yang lain yang membuat Anda berbeda dengan mereka semua. Berada di antara mereka yang seagama dengan Anda, identitas lain dalam diri Anda akan terpanggil untuk muncul dan membuat diri Anda merasa tak sama dengan mereka: Anda warga kota, seorang sarjana, dari keluarga kaya, dan seterusnya hingga pada titik di mana Anda tak bisa lagi secara bulat dipersamakan dengan mereka.
Kalau Anda berada di tengah keluarga dan sanak saudara sendiri, apakah itu berarti Anda berada di antara orang-orang yang samasekali tak berbeda dengan diri Anda? Anda seorang mahasiswa, sementara orang tua Anda adalah pegawai negeri, adik Anda seorang pelajar SMA, kakak Anda pegawai swasta, dan seterusnya. Anda berbeda dengan mereka semua, sekalipun ada banyak hal-hal yang membuat Anda sama dengan mereka, sebanyak perbedaan yang ada di antara Anda dan mereka. Anda memiliki identitas Anda sendiri yang tak pernah presisi dihadapkan pada identitas orang lain, bahkan dengan orang tua dan saudara sekandung atau saudara kembar Anda sekalipun. Anda adalah diri yang tak terpermanai. Anda adalah diri yang terus dirajut dan tak pernah selesai.
Sebagian kecil identitas Anda bersifat terberi (given) yang tak bisa dilepaskan, dan selebihnya adalah hasil konstruksi yang Anda rajut di sepanjang waktu kehidupan Anda. Yang satu terbentuk secara vertikal atau turun temurun, sedang yang lain tercipta secara horisontal lewat interaksi sosial. Anda yang terlahir dari orang tua berdarah Ambon, misalnya, tak bisa mengaku sebagai orang Jawa atau Sasak. Kesukuan adalah hal yang tak bisa ditawar ataupun dibentuk ulang, seperti juga golongan darah yang mengalir di dalam tubuh anda. Ia sepenuhnya terberi secara turun temurun. Namun Anda sebagai orang Islam atau Protestan atau Konghucu, juga Anda sebagai orang Indonesia, misalnya, tak tertutup kemungkinan untuk berpindah Agama ataupun berganti kewarganegaraan. Identitas yang horizontal seperti ini terlahir dari sebuah konstruksi yang di dalamnya terbuka ruang yang lapang untuk melakukan negosisi. Dalam identitas vertikal, Anda terpenjara di dalamnya untuk selamanya. Sebaliknya, Anda memiliki kebebasan penuh untuk meng(re)konstruksi identitas Anda yang bersifat horizontal. Dalam ruang horizontal inilah identitas Anda tak pernah selesai untuk diungkapkan, dan terus menerus dirajut dan diperbarui di sepanjang rentang kehidupan.
Identitas yang dilematik
Bayangkan seandainya Anda dilahirkan seorang ibu yang Dayak dan ayah Anda orang Madura. Di dalam diri Anda mengalir darah Dayak dan Madura. Anda adalah hibrida dari dua suku berbeda. Tapi apa nama atau sebutan kesukuan yang pas untuk mengungkapkan pertautan dua identitas berbeda yang melekat dalam diri Anda tersebut? Apakah pertautan itu menghasilkan sebuah etnisitas yang baru dan memiliki nama tersendiri? Kalau suatu saat Anda ditanya apa suku Anda, akankah Anda jawab bahwa Anda separuh Dayak dan separuh Madura? Sulit membayangkan bahwa identitas kesukuan seseorang harus—dengan terpaksa—dibelah-belah sedemikian rupa. Terlahir dari orang tua berbeda suku tidak otomatis membuat Anda memiliki identitas kesukuan yang setengah-setengah. Anda adalah diri Anda sendiri yang berbeda dengan orang lain, bukan setengah Dayak separuh Madura, sekalipun Anda juga bukan Dayak sepenuhnya atau Madura utuh. Ada perpaduan etnisitas yang khas di dalam diri Anda sekalipun itu tak terungkapkan dan tak terdefinisikan oleh keterbatasan sebutan etnisitas yang tersedia. Dan jika saja dulu Anda berada di Kalimantan Tengah tatkala pecah konflik berdarah antara suku Dayak dan Madura, di posisi mana kira-kira Anda akan berdiri seandainya Anda dipaksa untuk memihak salah satunya? Benar, bahwa dalam situasi demikian, identitas adalah sesuatu yang amat membingungkan dan menjadi beban berat yang tak bisa dilepaskan serta sarat dengan dilema.
Menghadapi represi, kata Maalouf, orang akan berusaha memilih salah satu identitas di dalam dirinya yang akan ia tonjolkan untuk menggalang persatuan dengan sesamanya di dalam kelompoknya, dan sekaligus menegaskan perbedaannya dengan pihak yang berdiri secara diametral dengannya. Orang Syiah akan menggalang persatuan atas nama ke-Syiah-annya ketika menghadapi ancaman dari golongan Sunni, juga sebaliknya, meskipun mereka sama-sama muslim dan sama-sama warga negara Irak. Di Maluku, dalam kurun waktu 1999-2002, orang Islam dan Nasrani saling bunuh. Padahal mereka sebelumnya hidup rukun berdampingan, demikian juga saat ini mereka hidup damai. Dalam kurun waktu itu pula, di Jawa, Sumatera dan tempat-tempat lain, Muslim dan Nasrani hidup berdampingan tanpa ada konflik berdarah, meski di Maluku keduanya saling menyingkirkan.
Benar bahwa identitas bukan faktor tunggal pemicu konflik di tengah-tengah masyarakat. Tapi tak bisa dipungkiri bahwa melalui sentimen identitaslah konflik dengan amat mudah dikobarkan hingga berdarah-darah. Entah itu dalam bentuk sentimen etnisitas, agama, rasial, kebangsaan maupun kedaerahan. Identitas apapun tak pernah bisa menyatukan banyak orang secara permanen, sebagaimana ia juga memecahbelah banyak orang secara temporer.
Dalam konteks konflik identitas, Cynthia Weber mengajukan apa yang disebut sebagai Logic of Representation untuk menganalisanya. Melalui logika representasi, ungkap Cynthia, orang atau kelompok berusaha memberikan gambaran kepada dirinya (self) dan kepada orang atau kelompok lain (others). Self mengembangkan logika yang positif terhadap dirinya sendiri sembari di sisi lain ia membangun logika yang negatif terhadap pihak lain. Pihak sendiri dianggap sebagai yang benar, sementara pihak lain dipandang sebagai yang salah dan mengancam. Dengan logika negatif dalam memandang pihak lain, self berusaha menggalang persatuan di dalam dirinya sembari mengonstruksi pembenaran untuk melakukan konfrontasi terhadap pihak lain yang dianggap mengancam tersebut. Dalam hal demikian, tafsir terhadap kebenaran berusaha dimonopoli masing-masing pihak untuk mempertahankan eksistensi diri—dan kerapkali—dengan cara melumatkan mereka yang dianggap salah dan mengancam. Tiap kelompok menganggap diri sendirilah yang paling benar, semua yang di luar dirinya adalah salah dan musti disingkirkan.
Dalam sejarah, pernah muncul ide mengenai pemurnian ras. Sebuah upaya menggagas identitas yang tunggal dan sekaligus membentenginya dari pengaruh yang lain, agar ia lestari dan tak tercemar oleh keburukan dari mereka yang memiliki identitas lain. Ide ini dulu dipraktekkan oleh rezim Nazi Hitler di Jerman dengan cara memusnahkan kaum Yahudi. Dengan mengasosiasikan ras Yahudi dengan hal-hal buruk yang dianggap mengancam eksistensi ras Arya, rezim Nazi membangun kamp-kamp konsentrasi untuk menghabisi mereka. Dalam ajaran Hitler, Arya adalah ras unggul sedangkan Yahudi adalah ras rendah yang tercela dan tak boleh dibiarkan melebur berbaur dengan ras Arya. Jerman hanya milik dan untuk orang Arya. Dan atas nama pemurnian identitas rasial inilah jutaan orang Yahudi dimusnahkan dalam kamp-kamp kerjapaksa—sesuatu yang tak pernah terjadi sebelum Hitler berkuasa maupun sesudah kejatuhan rezimnya di akhir Perang Dunia kedua.
Dalam konflik yang digerakkan oleh sentimen identitas, orang akan kehilangan individualitasnya. Orang akan memandang diri sendiri dan orang lain sebagai kolektivitas. Kalau Anda seorang WNI yang sedang berada di Malaysia, misalnya, Anda harus bersiap menerima perlakuan tak menyenangkan dari beberapa aparatur di sana. Di sana Anda hanya dikenali sebagai orang Indonesia yang diidentikkan dengan para TKI yang dianggap menimbulkan banyak masalah oleh pemerintah Malaysia. Mereka tak mau tahu bahwa sebenarnya Anda adalah orang baik-baik dan berpendidikan sarjana, misalnya. Di sini prasangka terhadap kolektivitas membuat Anda sebagai individu baik-baik akan kehilangan signifikansinya. Kekhasan dan keunikan diri Anda akan tersembunyi rapat-rapat. Anda hanya dikenali sebagai orang Indonesia, dan kemudian dipersamakan dengan para TKI yang dianggap biang keonaran di negeri jiran itu. Sebaliknya orang Malaysia pun akan cenderung menganggap semua orang Melayu adalah baik, meski sebenarnya ada juga yang suka membuat keributan. Orang akan pukul rata, menggeneralisir identitas individu-individu untuk memudahkannya dalam menimpakan prasangka kolektiv kepada pihak lain, dan di sisi lain memberi penilaian positif kepada pihak sendiri.
Dalam hal demikian, benar bahwa identitas adalah buah simalakama yang tak terhindarkan untuk ditelan oleh semua orang. Ia mempertautkan banyak orang dalam satu kurun waktu tertentu, tapi juga menceraiberaikannya di saat yang lain. Tak ada jaminan bahwa agama, etnisitas, ras, kebangsaan, kedaerahan dan aneka ragam identitas lainnya akan terus menerus mempertautkan dan menaungi banyak orang di dalamnya, sebagaimana ia juga tak selamanya menyeret banyak orang ke dalam sengketa yang melenyapkan banyak nyawa.
Sejatinya konflik memang hanya punya satu akar, yakni benturan kepentingan. Namun juga tak terbantahkan bahwa kepentingan seringkali melekat erat pada identitas. Perbedaan identitas mengandung perbedaan kepentingan di dalamnya, yang otomatis berpotensi memicu konflik. Dalam setiap sengketa, identitas akan kian dipertegas. Tembok pemisah antara ”aku/kami” dan ”dia/mereka” akan semakin diperkukuh. Tak ada lagi ”kita”. Dan atas nama identitaslah percikan api dengan mudah berubah menjadi lautan api. Perkelahian antar dua kelompok pemuda dalam sekejap mata berubah menjadi etnic cleansing yang berdarah-darah, membuat musnah ribuan nyawa dan harta benda. [*]
Wahyu Puspito S
07 Januari 2008.

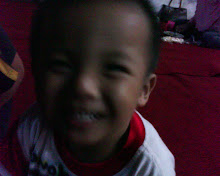
Tidak ada komentar:
Posting Komentar